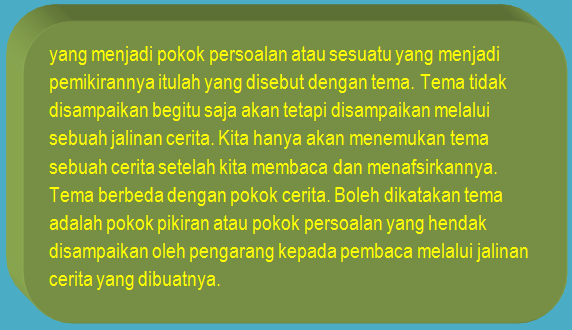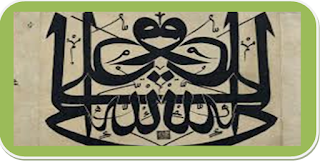Pengertian Amanat
Amanat merupakan maksud atau tujuan yang hendak disampaikan pengarang melalui karyanya, biasanya secara tersirat atau tersurat. Suroto (1990:89) mengatakan sebagai berikut:
“Biasanya untuk menyampaikan sebuah tema, penulis/pengarang tidak akan berhenti pada pokok persoalannya saja, akan tetapi disertakan pula cara pemecahannya atau solusi/jalan keluar untuk menghadapi persoalan yang ada. Hal ini sangat bergantung pada pandangan dan pemikiran pengarang. Pemecahan persoalan biasanya berisi pandangan pengarang tentang bagaimana sikap kita kalau kita menghadapi sebuahpersoalan tersebut. Maka hal yang demikian itulah yang dapat disebutkansebhagai amanat atau pesan dalam sebuah cerita”
 |
| Amanat dan Peristiwa Cerita dalam Sebuah Cerita |
(Baca Pengertian Cerpen dan Struktur Penulisannya)
(Baca Pengertian Jenis dan Tingkatan Tema dalam Sebuah Penulisan)
Kita tahu bahawa, Amanat pada umumnya terungkap melalui percakapan atau dialog tokoh dengan barisan pendampingnya, seperti tokoh lingkungan alam, bawahan, dan monolog berupa konfrontasi dengan jiwanya sendiri. Tokoh yang digambarkan berwatak humanis akan menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan saling kasih mengasihi sesama manusia. Tokoh koruptor biasanya digambarkan akan kalah, karena tidak bisa melawan kenyataan hidup yang dilandasi hukum dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.
Melalui karya sastra, seorang pengarang menumpahkan isi hatinya dengan maksud tertentu. Pengarang menyisipkan berbagai amanat dengan tujuan menyadarkan manusia dari kelupaan, mengingat kembali aturan yang berlaku, mengajak manusia untuk berpikir dan berzikir. Yang terpenting, pengarang menginginkan pembaca dapat menghayati amanat dalam karya sastra tersebut serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan pengarang mengemukakan masalah kehidupan dan sikap-sikap serta ajaran yang patut diteladani oleh pembaca supaya pembaca dapat mengikuti dan membedakan nilai ajaran yang patut diikuti dan nilai ajaran yang seharusnya dibuang. Dengan demikian, suatu karya sastra dapat dikategorikan bermanfaat atau bahkan sangat bermanfaat bagi dirinya sebagai pembaca. Di sinilah terbukti bahwa karya sastra itu memberikan kesadaran kepada pembacanya tentang kebenaran-kebenaran hidup ini. Karena dari karya sastra itu, dapat diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang manusia, dunia, dan kehidupan. Pembaca juga mendapat penghayalan yang mendalam terhadap apa yang selama ini telah diketahuinya.
Pengertian Peristiwa Cerita (Alur atau Plot)
Pengertian alur dalam cerpen atau dalam karya fiksi pada umumnya adalah jalan cerita yang dibentuk oleh urutan/tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh pelaku cerita dalam suatu cerita tersebut. Nurgiyantoro (2005:111) menyebutkan bahwa secara tradisional/masa dulu, orang juga sering mempergunakan istilah alur atau jalan cerita, sedangkan dalam teori-teori yang berkembang kemudian dikenal adanya istilah struktur susunan, naratif, susunan, dan juga sujet. Jenis penyamaannya begitu saja antara jalan cerita dengan plot, bahkan ada juga yang mendefinisikan plot sebagai jalan cerita, itu sebenarnya kurang cocok/tepat. Benar Plot memang mengandung unsur-unsur jalan sebuah cerita atau tepatnya urutan peristiwa demi peristiwa yang susul-menyusul, namun lebih dari sekedar jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut.
Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Nurgiyantoro, Sumardjo (2004:15) mendeskripsikan bahwa plot dengan jalan cerita memang tak dapat dipisahkan, tetapi harus dibedakan. Jalan cerita memuat peristiwa. Tetapi sesuatu peristiwa ada karena ada sebabnya, ada alasannya. Yang menggerakan peristiwa cerita tersebut adalah plot. Suatu peristiwa baru dapat disebut cerita kalau di dalamnya ada perkembangan kejadian. Suatu peristiwa berkembang kalau ada yang menyebabkan terjadinya perkembangan, dalam hal ini konflik.
Intisari dari plot memang konflik. Tetapi suatu konflik dalam cerpen tak bisa dipaparkan begitu saja. Harus ada dasarnya. Maka itu, plot dikupas menjadi elemen-elemen berikut: (1) pengenalan, (2) timbulnya konflik, (3) konflik memuncak, (4) klimaks, dan (5) pemecahan soal.
Unsur-unsur tersebut merupakan unsur plot yang berpusat pada konflik. Dengan adanya plot tersebut seperti di atas, pembaca dibawa dalam suatu keadaan yang menegangkan, timbul suatu suspanse dalam cerita. Suspanse inilah yang menarik pembaca untuk terus mengikuti cerita.
Menurut Sumardjo (2004:16), konflik digambarkan sebagai pertarungan antara protagonis dengan antagonis. Protagonis adalah pelaku utama cerita, sedangkan antagonis adalah faktor pelawannya atau tokoh lawan protagonis. Antagonis tak perlu berupa manusia atau makhluk hidup lain, tetapi bisa situasi tertentu, alam, Tuhan, kaidah norma, kaidah sosial, dirinya sendiri, dan sebagainya. Dengan demikian, kunci untuk plot suatu cerita adalah menanyakan apa konfliknya. Konflik cerita baru bisa ditemukan setelah pembaca mengikuti jalan ceritanya, yaitu aksi fisik yang dipakai pengarang menyatakan plotnya.
Dalam cerita fiksi atau cerpen, urutan tahapan peristiwa dapat beraneka ragam. Montage dan Henshaw (dalam Aminuddin, 2000:84), misalnya, menjelaskan bahwa tahapan peristiwa dalam plot suatu cerita dapat tersusun dalam tahapan exposition, yakni tahap awal yang berisi penjelasan tentang tempat terjadinyasuatu peristiwa serta perkenalan dari setiap pelaku yang mendukung cerita tersebut; tahap inciting force, yakni tahap ketika timbul kehendak, kekuatan, maupun perilaku yang bertentangan dari pelaku; rising action, yakni situasi panas karena pelaku-pelaku dalam cerita mulai berkonflik; crisis, situasi semakin panas dan para pelaku sudah diberi gambaran nasib oleh pengarangnya; climax, merupakan sebuah situasi klimax/puncak ketika konflik berada dalam kadar yang ter tinggi hingga para pelaku itu mendapatkan kadar nasibnya sendiri-sendiri; falling action, merupakan kadar konflik sudah menurun sehingga msalah/ketegangan dalam cerita tersebut sudah mulai mereda sampai menuju conclusion atau penyelesaian akhir cerita tersebut.
Selanjutnya, Nurgiyantoro (2005:142) menyatakan bahwa plot prosa fiksi, secara umum terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
(1) Tahap Awal
Tahap awal sebuah cerita biasanya disebut sebagai tahap perkenalan. Tahap ini biasanya berisi informasi awal tentang tokoh dan latar cerita. Dalam hal ini pengarang menunjukkan dan memperkenalkan, seperti nama-nama tempat, suasana alam, waktu kejadian, dan pengenalan tokoh cerita. Selain itu, pada tahap ini konflik sedikit demi sedikit mulai dimunculkan.
(2) Tahap Tengah
Tahap tengah disebut juga dengan tahap pertikaian. Dalam tahap ini pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya, menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. Pada tahap inilah inti cerita disajikan, tokoh-tokoh memainkan perannya masing-masing, fungsional /peristiwa-peristiwa penting dikisahkan, konflik berkembang semakin parah/meruncing, menegangkan/deg-degan, dan mencapai puncak/klimaks dan pada umumnya tema pokok, makna pokok cerita diungkapkan pula. Pada bagian inilah pembaca memperoleh ”cerita”, memperoleh sesuatu dari kegiatan pembacaannya tersebut.
(3) Tahap Akhir
Tahap akhir cerita disebut juga dengan tahap peleraian, menampilkan adegan tertentu sebagai akibat klimaks. Tahap ini berisi bagaimana kesudahan cerita atau menyaran bagaimanakah akhir sebuah cerita: kebahagiaan (happy ending) atau kesedihan (sad ending).