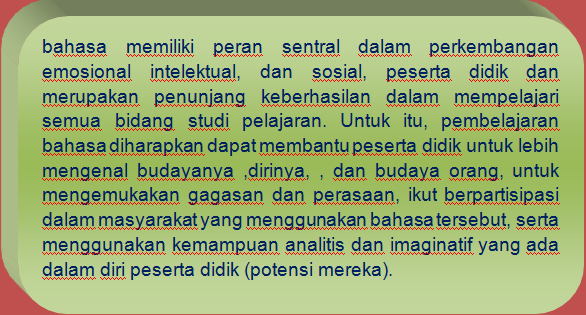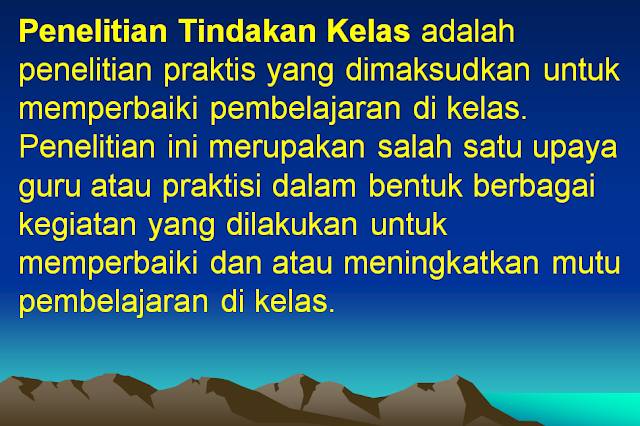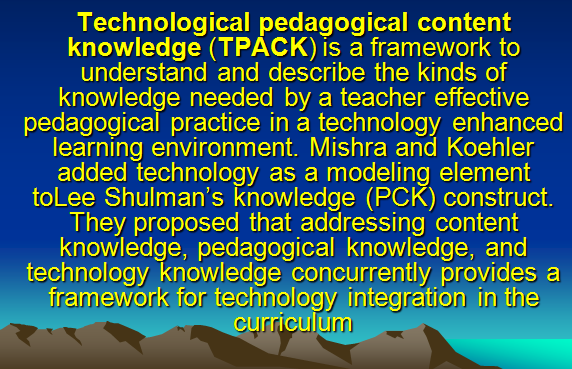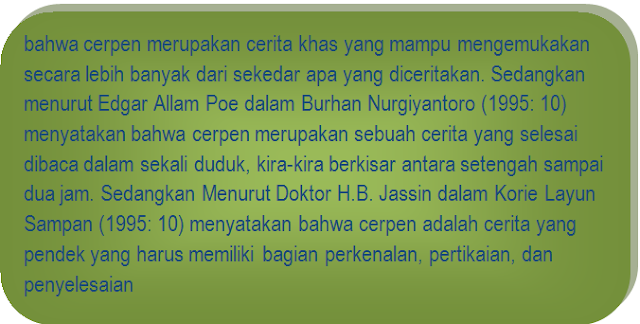Metode yang Tepat dalam Menulis Sebuah Naskah Drama. Seorang penulis harus mengetahui tehnik-tehnik untuk menulis sebuah naskah drama sebelumnya agar naskah yang ditulis menjadi bagus untuk dipentaskan. Menulis naskah drama tidak jauh berbeda dengan menulis cerpen maupun novel tetapi lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pengertian naskah drama itu sendiri. Luxemburg (dalam Depdiknas, 2004:170) mendefinisikan ‘Teks drama adalah sebagai semua teks yang berbentuk dialog-dialog. Disamping itu, Ia juga menuturkan bahwa terdapat tiga pokok yang perlu ditinjau dalam sebuah drama yaitu: situasi penyajian, alur dan bahasa’.
 |
| Metode Menulis Naskah Drama |
Selanjutnya, penulis harus mengetahui teknik-teknik penulisan drama yaitu sebagai berikut:
(1) Menciptakan setting (latar), (2) melakukan eksplorasi (pengamatan
dan pencatatan), (3) menulis latar, (4) menciptakan tokoh, (5) mendeskripsikan tokoh, (6) meletakkan tokoh dalam latar, (7) menciptakan tokoh berbicara, (8) penempatan semua elemen bersama-sama menjadi skenario dasar, (9) membuat skenario dasar (kasar): menyusun adegan, (10) menulis rangkaian adegan ke dalam draft dan (11) penulisan draf kedua: menulis kembali draft pertama. (Depdiknas, 2004:144)
(Baca Peranan Guru Dalam Pembelajaran Ketrampilan Menulis Paragraf)
(Baca Unsur-Unsur yang harus diperhatikan Dalam Menulis)
Oleh Waluyo (dalam Depdiknas, 2004:167-170) menyebutkan untuk menulis naskah secara lengkap dan rinci siswa harus memahami terlebih dahulu struktur drama yaitu:
(1) Plot atau kerangka cerita
Sebagaimana kita pahami, Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka/konsep dari awal hingga akhir sebuah cerita yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan (Antagonis). Konflik itu berkembang karena kontradiksi antara sifat dua tokoh yang berlawanan. Sifat dua tokoh utama yang bertentangan misalnya, kebaikan kontra kejahatan, tokoh sopan kontra tokoh yang brutal, tokoh pembela kebenaran kontra bandit, tokoh kesatria kontra penjahat dan sebagainya. Konflik itu semakin lama semakin meningkat kemudian mencapai titik klimaks. Setelah klimaks peristiwa tersebut akan menuju penyelesaian.
(2) Penokohan atau perwatakan
Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Susunan tokoh adalah daftar tokoh-tokoh yang berperan dalam sebuah drama. Dalam susunan tokoh yang terlebih dahulu dijelaskan adalah nama, umur, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan dan keadaan kejiwaannya. Penulis cerita harus menggambarkan perwatakan tokoh-tokohnya sehingga watak tokoh itu akan menjadi nyata terbaca dalam dialog dan catatan samping. Jenis dan warna dialog akan menggambarkan watak tokoh.
Watak para tokoh tersebut harus konsisten dari awal sampai akhir. Watak tokoh protagonis dan tokoh antagonis harus memungkinkan keduanya menjalin pertikaian sehingga pertikaian itu memungkinkan untuk berkembang menjadi klimaks. Kedua tokoh ini haruslah tokoh-tokoh yang memiliki watak yang kuat (berkarakter) sehingga watak yang kuat itu kontradiktif antara keduanya. Dapat juga keduanya memiliki kepentingan yang sama saling berebut sesuatu atau saling bersaing.
Sifat watak para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi (watak dimensional). Adapun Penggambaran tersebut berdasarkan keadaan psikis, sisoal dan fisik. Keadaan fisik biasanya dilukiskan pada awal baru kemudian dilaanjutkan keadaan sosial. Pelukisan watak pemain dapat langsung pada dialog yang mewujudkan watak dan perkembangan lakon tetapi banyak juga kita jumpai dalam catatan samping (catatan teknis).
(3) Dialog atau kosakata
Ciri khas suatu drama adalah naskah yang berbentuk percakapan atau dialog. Dalam menyusun dialog penulis harus benar-benar memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari mereka. adapun Pembicaraan yang ditulis oleh sipenulis naskah drama tersebut adalah pembicaraan yang akan diucapkan dan harus pantas untuk diucapkan di atas panggung wajtu pementasan. Bayangan pentas di atas panggung merupakan tiruan (mimetik) dari kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dialog yang ditulis harus mencerminkan pembicaraan sehari-hari.
(4) Latar atau landasan tempat kejadian.
Penulisan sebuah cerita tidak dapat ditulis jika di dalam imajinasi saja/tidak ada gambaran latar dari cerita tersebut. Baik itu yang bersifat geografis, budaya atau yang sangat abstrak sekalipun. Penentuan latar harus secara cermat sebab naskah drama harus memberikan kemungkinan untuk dipentaskan. Novakovich (dalam Depdiknas, 2004:118) menyebutkan bahwa: ‘Latar adalah sarana utama karena dari latarlah kemudian muncul tokoh dan dari tokoh kemudian munculah konflik sehingga tercipta alur cerita’.
Harus dipahami, bahwa latar seniah cerita biasanya meliputi tiga dimensi yaitu waktu, runag dan tempat. Latar tempat tidak akan dapat berdiri dengan sendirinya berhubungan dengan waktu dan ruang. Misalnya tempat di Aceh, tahun berapa, di luar rumah atau di dalam rumah. Untuk cerita konflik antara RI dan GAM misalnya, tempatnya jelas di Aceh, pada tahun 1998-2005, tempatnya di desa, baik di dalam rumah maupun di medan gerilya. Dengan rumusan tersebut kita dapat membayangkan tempat kejadian secara nyata. Hal ini dapat diperkuat dengan kostum, tata pentas, make up dan perlengkapan lainnya jika drama ini dipentaskan.
(5) Tema atau nada dasar kejadian
Tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema bersifat lugas, objektif dan khusus. Ada drama yang diantaranya bertema ketuhanan, peri kemanusiaan, cinta, patriotisme, kritik sosial, renungan hidup dan sebagainya.
(6) Amanat atau pesan pengarang
Kita paham jika Amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui dramanya harus dicari oleh pembaca atau penonton itu sendiri. Seorang pengarang drama baik secara sadar atau tidak sadar pasti menyampaikan amanat dalam karya mereka. Pembaca yang cukup teliti akan dapat menangkap apa yang tersirat di balik yang tersurat. Amanat bersifat kias, subjektif dan umum. Untuk itu, Setiap pembaca dapat dengan berbeda-beda menafsirkan makna dari karya itu bagi dirinya, dan semuanya cenderung dibenarkan kerana tidak ada batasan salam menafsirkannya. Amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang perlu diberikan beberapa alternatif dan di dalam menafsirkan amanat penikmat dapat bersifat akomodatif.
(7) Juknis (Petunjuk teknis)
Sebaiknya, dalam naskah drama diperlukan juga petunjuk-petunjuk teknis yang sering disebut dengan teks sampingan. Senagaimanan kita amiti dalam sebuah sandiwara radio, sandiwara televisi atau skenario film, keberadaan teks samping ini sangatlah penting dalam sebuah pementasan drama. Itu karena teks samping ini memberikan petunjuk teknis tentang suasana pentas, tokoh, waktu, musik, suara, keluar masuknya aktor atau aktris, warna suara dan perasaan, keras lemahnya dialog yang mendasari sebuah dialog dalam drama tersebut. Teks samping ini biasanya ditulis dengan tulisan berbeda dari dialog, misalnya dengan huruf miring atau huruf besar semua.
(8) Drama sebagai interpretasi kehidupan
Ulasan tentang drama sebagai interpretasi kehidupan sangat erat hubungannya dengan pandangan dasar dri si penulis drama itu sendri. Kita tahu bahwa nada dasar drama bukan nada dasar penafsir atau sutradaranya sendri. Jadi drama sebagai hasil dari tiruan kehidupan berusaha untuk memotret kehidupan secara nyata (real). Untuk itu, maka Setiap pengarang tidak sama dalam mengamati, melihat dan menginterpretasikan sisi kehidupan yang ada. Ada pengarang yang memfokuskan pada segi keadilan, segi cinta kasih, segi kebobrokan sosial, segi moral, segi didaktis, segi kepincangan dalam masyarakat, segi suka atau duka dan sebagainya. Tontonan atau naskah yang dihasilkan akan ditentukan oleh bagaimana sikap penulis dalam menginterpretasikan kehidupan ini.